
Ditulis Oleh:
Cikgu Mohd Hashim Osman.
(B.Ed (Hons) Kesusasteraan Melayu, UPSI).
Kakitangan Jabatan Bahasa SMK (F) Besout.
hashim@smkbesout.edu.my
BERAT akal untuk memikirkannya, berat lagi untuk jiwa menyambut memenuhinya. Kerja ini bukan saja sudah dikira menceroboh sempadan, tetapi lebih berat lagi mencabar sempadan intelektual dan kewibawaan pribumi.
"Kasihanilah kami. Sekian lama bangsa kami ditindas birokrasi dan autokrasi di sebalik nama kebajikan. Aku hanya perlukan tenaga akalmu, bukan tenaga fizikalmu, " rayunya.
Setiap patah ucapanmu kuamati sepanjang pertemuan sulit itu. Segala biayaan penerbangan, penginapan, dan makan minum akan diuruskan sebelum aku bertolak meninggalkan tanah air.
Penginapanku, sebuah rumah inap yang sederhana. Betul-betul menghadap laut sebelah barat. Sesuai dengan title kehadiranku sebagai karyawan dan pemancing. Pemiliknya, ibu Suria kulihat tenang dan jujur kala menerima kehadiranku.
Lewat tingkap sebelah barat, jelas terdengar debur ombak memutih saling berlumba mengejar pantai. Mengasyikkan. Di gigi pantai itu nanti, atas bongkah-bongkah batu hitam, joran-joran yang kubeli khusus akan mengisi senggang waktu - sebenarnya telah dijadualkan, di sebalik teluk yang terlindung oleh bukit kecil ada sebuah pelabuhan untuk memunggah barang. Di luar rekod, manusia juga boleh dipunggah secara gelap.
"Baru-baru ini, satu lagi mangsa penindasan Presiden. Imam Jumri!" Putera muncul lewat malam pada hari pertama.
"Jumaat lalu, Imam Jumri dengan berani mengkritik Presiden dalam khutbahnya. Subuh esoknya, Imam Jumri tidak muncul-muncul. Setelah disusuli, isterinya memaklumkan, Imam dijemput seseorang lewat malam Jumaat itu," bersemangat dia bercerita.
Menurutnya, selepas tiga hari Imam Jumri kembali dengan wajah sugul dan guram. Mengeluh, merungut, menggeleng dan menangis. Hari keempat, dia kembali menemui Tuhan dengan sesak nafas. Entah apa yang telah Presiden lakukan terhadap orang tua itu.
Tanpa mahu mengulas, lantas aku bentang susun atur langkah perjuangan sahabatku itu. Cepat matlamat perjuangannya tercapai, boleh cepat aku angkat kaki dari bumi asing ini. Dulu, dua dekad lalu, strategi dan susunan kerja yang kurancang berjaya menjulangnya sebagai pemimpin pelajar di universiti selama dua penggal menumpaskan calon favourite, siswa tempatan tajaan pihak pentadbir universiti bereputasi tinggi di sebuah negara timur tengah.
Sebenarnya pengalaman arwah ayah jadi teras strategiku. Strategi ampuh arwah ayah sebagai nasionalis, telah menunjuk jalan pulang kepada kolonialis barat. Susun atur yang sama kini masih jadi taruhanku membantu Putera menumbangkan seorang Presiden negara berkapasiti sepuluh juta warga.
Kutitip tunjang utama strategi: Simpati adalah umpan paling berkesan terhadap perjuanganmu.
"Bagaimana?"
Kalau kau berjaya bina jambatan persefahaman dengan tiga institusi ini, pasti Presiden yang kau bilang berkuku besi itu akan melutut tewas.
Namun sejarah tetap sejarah. Sejarah manis hanya seketika yang kemudiannya terpaksa kami telan dengan penuh pahit. Ayah disingkir penuh tragis dari harakah fikrahnya sendiri. Ayah dikhianati sahabat sendiri, menghembus titik kehidupannya dalam tahanan.
"Tiga institusi?"
Ya, tiga institusi ini kalau dikuasai hatinya, kalau dikuasai akalnya, sudah merangkumi dua pertiga kuasa rakyat. Aku menoleh sejenak melewati tingkap sebelah utara. Samar-samar lampu utama astana Presiden di Bukit Mercu menarik pandanganku.
*******Ruang mewah sebuah kediaman dua tingkat di penjuru negara jadi titik pertemuan rahsia pertama gerakan Putera. Milik seorang tokoh korporat.
Putera sudah dapat membaca resah hati tokoh korporat, teman sekolahannya itu. Kekecewaannya jelas mendongkol apabila usahanya menggali bijih besi di tanah air sendiri tidak diluluskan oleh Presiden.
Putera berjanji, projek mega temannya akan menjadi sumber utama pendapatan negara dengan di bawah penguasaannya nanti. Industri bijih besi itu bukan sahaja lumayan cukainya, tapi yang lebih utama dapat menyuntik peluang pekerjaan kepada ribuan anak negeri.
Empat tokoh belia yang dijemput, datang menagih harapan tinggi harapan kepada Putera. Perutusan lisannya kepada Putera menggambarkan rasa kecewa golongan belia di negara itu.
"Di negara-negara jiran, belia seusia kami hidup mewah dan bergaya. Pendapatan bekerja di kilang-kilang perusahaan yang tumbuh melata sungguh-sungguh memikat. Peluang pinjaman rumah, kerat dan peribadi dibuka seluas-luasnya. Tapi, kami di sini dikerah memugar tanah untuk berladang-ladangan, bersawah-sawahan dan dikerah ke laut. Apakah wajar ijazah yang kami miliki hanya untuk berlodak, berlumpur dan dilambung ombak?"
Tiga teman di sebelahnya mengangguk.
"Dasar ekonomi terkawal Sang Presiden membantutkan kedatangan pelaburan asing . Kilang-kilang dibina jauh di pinggiran negeri. Kononnya demi kestabilan udara dan alam sekitar. Ahh....mengarut!"
Putera menggeleng kepala. Simpati akan nasib institusi belia. Janji Putera, segala kemewahan hanya dapat dikecap setelah Sang Presiden dilumpuhkan kuasanya.
"Presiden zalim. Bakat kami langsung tidak dipandang. Aktiviti, persembahan hanya dibenarkan di premis-premis tertutup dan terpencil. Premis-premis yang hanya dikunjungi buruh-buruh asing yang ketagihan samsu."
Meluap-luap kemarahan ditunjukkan oleh wakil penggiat-penggiat muzik underground yang dipanjat tua. Rantai yang melilit leher, gelang kulit di kedua-dua pergelangan tangannya serta jaket kulit masam yang menyengat hidung, menggambarkan ketidakpeduliannya akan nilai budaya bangsanya.
"Mujurlah pasaran seni dan bakat kami dihargai negara-negara jiran. Lebih banyak ruang kami di sana. Pelakon-pelakon kita laris ditangan produser-produser luar. Tapi... segalanya hanya hujan emas di negeri orang." 'Remaja' separuh umur itu memberi tabik sebelum duduk.
Putera memberi keyakinan kepada kelompok seni yang terpinggir itu.
Sejenak, dia menoleh lelaki di sisi kirinya. Lelaki berkaca mata gelap, bersweater gelap dengan tubir hutnya sengaja diturunkan ke paras keningnya. Sejak munculnya tadi, wajah berjambang palsu asyik menekur ke muka i-pad di hadapannya.
*******Lewat petang aku sampai di muka laman rumah inap. Disambut Ibu Suria dengan senyum, aku lantas tertangguh untuk menjejak anak tangga. Matanya lekat seketika pada peralatan pancingku dan beralih ke arah beg sandang yang baru kuletakkan di anak tangga.
"Kalau memancing di pantai, paling kurang jorannya panjang 13 kaki, baru lontaran pergi jauh. Tidaklah sangkut pada batu-batu yang bercerakah di tepi pantai."
Kembang wajahku. Malu.
"Batu ladung yang anak guna ini, tak cukup untuk melawan arus air yang deras di dasar laut. Kalau nak lebih tahu, jumpalah Pak Misron. Laut, mainannya sejak kecil."
Aku mengangguk.
"Putera tak tahu apa-apa pun tentang laut..." jantungku diterjah ungkapan ibu Suria. "Tiga suku hidupnya di negara asing. Usahkan bahasa ombak, jenis ikan dan karangpun dia mangkar. "
Pantas aku mengalih mata, pura-pura terpukau dengan pohon sinar barat yang membuahkan senja.
"Di sini, nikmat alam ini adalah milik bersama. Sesiapa saja bebas memancing, menjala, berenang, bermain ombak tanpa ada sekatan. Apa gunanya pesisir ini dibangunkan, kalau akhirnya kebebasan kami dibatasi tembok eksklusif yang tebal dan kebal."
Di katil perbaringan pada malam itu, kuliah senja Ibu Suria bermain-main di benak.
Kunci kekayaan persisiran pantai sebelah barat bumi ini memang sentiasa diintai ramai hartawan hartanah dalam dan luar negara.
Benar, penginapan mewah dan separa mewah mampu menghadiahkan banyak peluang kerja. Benar, pembangunan industri pantai yang rancak turut memangkin industri kecilan anak tempatan. Namun, pengalaman negara-negara jiran sudah cukup mengajar.
Peluang kerja berpindah ke tangan imigran-imigran murahan. Gerai kraftangan di pinggiran bertukar menjadi gerai minuman keras, kononnya menjaga hati pengunjung asing. Ketika imigran asing gigih mengumpul laba, pemuda tempatan terkulai di celah-celah botol. Anak-anak gadis kemaruk dengan dakapan nafsu lelaki-lelaki asing. Harga barangan keperluan harian melambung. Nelayan kecil diikat oleh pemborong yang memanipulasi harga. Akhirnya, kapitalis-kapitalis mendominasi negara.
"Kami, pribumi akhirnya akan jadi hamba di bumi sendiri. Itulah kebimbangan Presiden."
Jemariku kelu di muka papan i-pad.
*******Riak-riak kebangkitan gerakan Putera sudah tidak dapat ditahan-tahan, mengalir cepat menakluk hati. Dari sebuah gerakan picisan, langkah Putera mula menjejak ke arus perdana. Anak-anak muda kecanduan meneguk janji Putera.
Malah, tidak kurang, dalam senyap sebilangan pegawai-pegawai Presiden mula beralih sokongan.
"Kunci astana Sang Presiden makin hampir pada genggaman. Akan kita selongkar segala khazanah negeri yang bertapuk bilik-bilik perbendaharaan astana. Akan kita hidangkan khazanah itu untuk kalian menikmati bersama-sama. Astana Presiden akan kita isytiharkan Astana Rakyat!" sorakan bergema ke langit.
Pentas ucapan Putera kian menggegar.
Dalam ghairah itu, Putera sedar, apa sahaja boleh berlaku. Dengan perancangan rapi, dia sudah bersedia menunggu tindak balas Presiden. Kala itu nanti, gelombang simpati rakyat akan bangkit membela nasib Putera. Gelombang itu, akan pasti menamatkan nasib dinasti Presiden.
Putera kurasakan sudah mampu bergerak sendiri dengan rakan-rakan juangnya. Dengan penuh hati-hati, dengan langkah tersusun, aku menjarakkan diri daripada pautan Putera. Pengalaman pahit arwah ayah tetap kupegang.
Seminggu belakangan, ketika gelombang rakyat kian membuak, masa senggang Maghrib melewati Isyak, aku dekati masjid lama pinggir kota. Tidak jauh dari Astana Presiden. Masjid yang hanya ditaati oleh jemaah-jemaah separuh umur.
"Di situ, kamu boleh mendekatinya. Dia mengenali rapat Presiden. Pantas membaca, cepat mengerti segala dasar Presiden untuk negara. Banyak bahan boleh kamu gali untuk mengungguli karya-karyamu nanti," pesan Pak Misron.
Wajahnya sentiasa terlindung oleh kain yang dilepas labuh menutup wajah dari pandangan sisi. Dia, Pak Darwis kuperhatikan hanya akan muncul menjelang sepuluh atau dua puluh minit sebelum azan Isyak.
Malam ketiga baru dapat aku mendekatinya seketika. Itupun lama menunggu untuknya selesai solat-solat sunat dan berzikir. Pada malam kelima, aku agak terkejut apabila tiba-tiba dipelawa mengiringi ke penginapannya. Malam pekat, dan perjalanan kami hanya dipandu oleh kebiasaan Pak Darwis dan biasan sinar bintang-bintang di langit.
"Karyawan seperti kamu amat dihargai Presiden. Katanya, karyawan memiliki kekuatan ilmu dan pemikiran yang tidak ada pada sembarangan orang. Setiap karya anak tempatan yang berkualiti dipampasi kerajaan dengan harga yang tinggi. Karya-karya itu disimpan sebagai khazanah negara." Daripada berhati-hati, suara Pak Darwis kian rancak.
Cemburuku bertapuk kerana di tanah airku karyawan hanya dianggap barisan insan kelas tiga. Hadiah sayembaranya tidak lebih daripada satu perempat nilai hadiah ketiga peraduan hiburan realiti atau sayembara memancing yang tak punya manfaat apa-apa kepada warganya.
Agak lama berjalan, aku tidak sedar sudah sampai ke destinasi. Suasana gelap tidak membantuku untuk melihat persekitaran. Sebaik pintu di buka lampu suram menerpa. Tiada sebarang meja atau kerusi. Aku dipelawa duduk. Bersila.
Dua pemuda berjubah lusuh berusia awal dua puluhan kulihat muncul menatang hidangan. Mereka kemudiannya diperkenalkan sebagai anak-anak Pak Darwis. Walaupun cuma sebuku roti bercicahkan kuah kosong, keikhlasan Pak Darwis cukup membuatkan aku berselera. Ahh... sesuatu yang diluar jangka, lelaki yang kulihat hanya seorang pinggiran, begitu jauh mengenali Presiden. Tentang Putera, Pak Darwis hanya menggeleng kepala.
"Presiden sudah tak ambil pusing tentang bekas anak angkatnya, yang pernah ditatangnya pada suatu masa dulu. Putera tak tahu apa-apa sebenarnya." Di sebalik sinar lampu kelam, ada genangan di kelopak mata Pak Darwis.
Lewat malam, salah seorang anak Pak Darwis menemaniku pulang hingga persimpangan penginapanku.
*******Putera tawan Astana Presiden!
Mesej itu sekali gus menarik perhatianku melayari maya lewat teknologi i-pad. Aku menarik nafas lega yang panjang. Jelas, langkah atur yang kususun selama hampir dua bulan banyak membantu gerakan Putera ke puncak kejayaannya. Sebaik menjejak lantai geladak lewat malam tadi, pantas kad sim telefon selular kulempar ke muka laut. Nekad aku tidak mahu dihubungi.
Gerombolan Putera melangkah ruang laman Astana Presiden menjelang senja kelmarin. Serentak itu tanpa pamitan, aku segera menyusur pergi sebaik sahaja selesai menunaikan solat maghrib. Tugasku sudah selesai.
Aku sudah tidak mahu campur lagi. Biarlah Putera menyelongkar Astana idamannya. Biarkan Putera membongkar segala kekayaan yang dikatakan tersembunyi di mana-mana ruang istana.
Satu persatu gambar kejayaan dan penyelongkaran Putera di Astana terpamer di skrin. Entah mengapa aku tidak teruja dengan gambar-gambar kejayaan sahabatku itu.
"Assalamualaikum...!"
"Wa..waalaikumssalam. Masya-Allah... Pak Darwis?"
Inilah kali pertama dapat kutatap wajahnya secara jelas. Sejuk, bercahaya. Tanpa dipinta, dia memberitahu bahawa langkahnya sekeluarga agak baik kerana sempat menjejak geladak sebelum kapal barang ini bertolak. Maknanya aku sedikit awal. Namun kami tidak terserempak kerana aku segera berehat di atu sudut yang agak terlindung.
"Jangan terpedaya dengan gambar-gambar dan berita-berita maya tentang penyelongkaran Astana itu. Lebih tiga suku hanyalah propaganda dan kepalsuan," lembut Pak Darwis melontar bicaranya.
"Tidak ada jongkong emas, tidak ada timbunan wang, tidak ada kemewahan seperti yang dikhabarkannya itu. Percayalah, yang ada hanyalah naskhah-naskah pemikir dan cendekiawan yang amat-amat dihargai oleh Presiden lebih daripada segala-galanya."
"Arwah Imam Jumri sudah saksikan sendiri. Kamu juga sudah saksikan sendiri betapa ruang makan milik Presiden sendiri yang tidak punya apa-apa. Hatta untuk makan malam pun, Presiden dan keluarganya hanya berkongsi dua buku roti. "
"Maksud Pak Darwis?" rusuh menekan dadaku.
"Sayalah Presiden, yang digulingkan...!"
Ya Allah.... Dalam samar, kulihat Putera sedang terpaku di tengah delusi. Delusi sebuah astana.
Sumber:http://www.utusan.com.my/ ARKIB : 19/02/2012



.jpg)
























+(2).jpg)








.jpg)



Imej262.jpg)


.jpg)




.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
jelawat+epoi.jpg)

.jpg)








































.jpg)





























































.jpg)







































































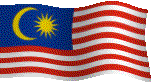


Tiada ulasan:
Catat Ulasan